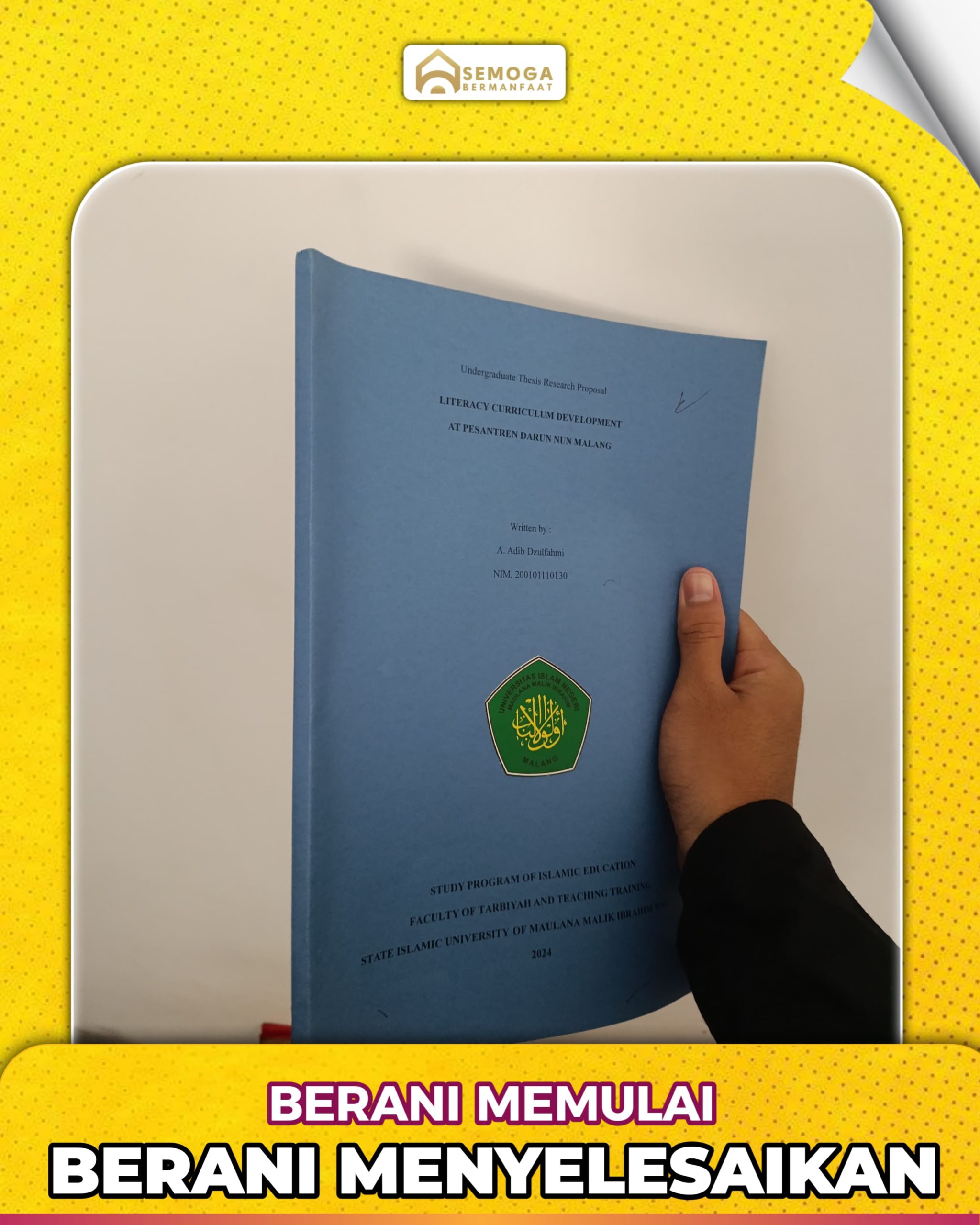Malaikat Rumahku: Ibu dan Pelajaran Hidup yang Abadi

“Nak, jika sudah besar cita-citanya menjadi apa?” Tanya ibu dengan tatapan cintanya
Tanpa ragu, aku menjawab “Kalau sudah besar aku ingin seperti Aa Gym kayak uang di 5.000 itu.”
Pertanyaan dan harapan yang sampai saat ini masih membekas di ingatanku tentang sosok idolaku saat kecil.
Ibu hanya tersenyum, sambil mengusap kepalaku dengan lembut. Saat itu, aku tidak tahu bahwa sosok yang ada di uang 5.000 bukanlah Aa Gym. Namun, bagiku, Aa Gym adalah sosok yang aku idolakan sejak kecil dengan dakwahnya yang damai, lembut, dan penuh keteladanan.
Aku lahir dari rahim seorang ibu yang penuh cinta, sayang kepadaku. Seorang yang lahir di sebuah desa kecil pertatasan 2 kabupaten dan berada di ujung Provinsi Jawa Barat berbatasan Jawa Tengah. Lahir di tengah keluarga yang sederhana dan di kampung membawaku untuk tumbuh lebih dewasa dan menjadi pribadi yang mandiri.
Setiap malam, sebelum tidur, ibu selalu membelai kepalaku dengan penuh kelembutan. Dalam gelap yang tenang, suaranya menjadi melodi terindah yang mengantarku terlelap.
Ibu bercerita tentang banyak hal tentang perjalanan hidupnya, perjuangan menghadapi kesulitan, atau sekadar kisah kecil yang ia alami di siang hari. Tak jarang, ia juga menceritakan kisah-kisah penuh hikmah, tentang perjuangan para nabi, ulama, atau orang-orang yang menginspirasi.
Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, meski sering kali tak sadar kapan aku mulai tertidur di tengah cerita itu. Suara ibu adalah kehangatan yang selalu kutunggu setiap malam, suara yang menenangkan dan memberikan rasa damai.
“Nak, jika sudah besar nanti jadilah orang memberi manfaat, jadi seorang yang bisa membanggakan orang tua”. Pesan yang terus melekat sampai sekarang. Moment yang sangat dirindukan saat ini setiap pulang dari tanah perantauan.
Setiap pulang ibu selalu ada cerita baru tentang masa kecilku. Pernah suatu ketika bercerita tentang dulu jika makan hanya cukup dengan kerupuk dan kecap, karena saat itu keluargaku belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan cukup.
Ada satu cerita yang selalu membuatku tertawa setiap kali ibu menceritakannya. Waktu itu, aku masih berusia sekitar 3-4 tahun. Saat itu, aku lari-lari mengejar ibu dan bapak yang hendak pergi ke kondangan, padahal aku belum memakai baju atau celana. “Nak, kamu kok ikut? Kok lari-lari telanjang begitu?” tanya ibu sambil tersenyum, mengenang kejadian itu.
Menangis dan kecewa. Itulah perasaanku bukan karena tidak sayang namun karena tahu setiap diriku ikut ke kondangan, pasti beli mainan. Hehehe. Bukan masalah mahal atau tidaknya namun saat itu uang yang dibawanya pas-pas an. Ingin rasanya kembali dan mengingat kembali waktu itu.
Perjalanan hidup yang tidak pernah usai akan cerita, membawa keluargaku hidup untuk pindah rumah disaat umurku berusia 6 tahun. Sebenarnya ini bukanlah keinginanku atau keluarga namun tuntutan pekerjaan untuk mencari rumah yang lebih dekat dari rumah. Tidak hanya sekali, tiga kali berpindah rumah sehingga membawaku untuk mendapat cerita dan teman baru. 13 tahun hidup di lingkungan bahasa dan budaya yang berbeda, yaitu “Jawa Koek/Ngapak” orang sini biasa menyebutnya. Namun tak pernah ku sesali kenapa mesti berpindah rumah dan berganti lingkungan.
Kasing dan Sayang Ibu, pernah suatu saat ketika ibu sedang memasak. Diriku ingin mencoba memasak dan membuat resep makanan yang baru lihat di Youtube. Dengan penuh semangat, aku mulai menyiapkan bahan-bahan di meja. Namun, kecerobohanku membuat sebuah piring berisi bumbu tersenggol. Dalam sekejap, suara pecahan piring menggema di dapur, berserakan di lantai. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Aku menatap ibu, takut dimarahi.
Namun, ibu hanya tersenyum. Tidak ada nada tinggi, tidak ada teguran keras, hanya tatapan penuh kasih dan suara lembut yang menenangkan.
“Nak, kamu tidak apa-apa? Ada yang kena, berdarah?” tanyanya sambil mendekat, memastikan tanganku tak terluka.
Aku tergagap, masih merasa bersalah. “Tidak kenapa-kenapa, Bu! Maaf tadi menyenggol sehingga jatuh dan pecah.”
Ibu menggeleng pelan. “Nggak apa-apa, piring bisa beli lagi, yang penting kamu nggak terluka.”
Aku tertegun. Ibu lebih peduli padaku daripada pada piring yang pecah. Padahal, aku tahu, di rumah kami barang pecah tidak mudah diganti begitu saja. Namun, baginya, keselamatanku jauh lebih berharga dibandingkan benda apa pun di dunia ini.
Ibu tidak memarahiku karena baginya, kesalahan adalah bagian dari belajar. Ia tidak menegur dengan suara keras, karena baginya, kata-kata yang lembut lebih bermakna. Ia tidak menghukumku, karena ia tahu bahwa rasa bersalahku sudah cukup menjadi pelajaran.
Itulah ibu. Seorang perempuan yang menjadi Malaikat rumahku yang tak pernah sekalipun aku melihatnya marah. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali ibu membentakku atau mengeluhkan sesuatu. Tidak ada. Sejauh ingatanku, ibu selalu menanggapi segala sesuatu dengan tenang, dengan senyum yang selalu ia hadiahkan kepada siapa saja yang menemuinya.
Ibuku merupakan lulusan Pesantren Darussalam Ciamis sehingga berharap untuk setiap buah hatinya bisa melanjutkan pendidikan formal dan non formalnya di Pesantren. Pondok Pesantren merupakan rumah keduaku. Pesantren Miftahul Anwar Dampasan menjadi pilihan ibuku, sampai ketika pertama kali diantar ke Pondok ibu berpesan.
“Nak belajar yang tekun karena ilmu itu ringan untuk dibawa” sambil mengelus kepalaku dan berdoa dengan penuh harap.
“Maksudnya gimana bu?” Dengan penuh rasa heranku bertanya
Aku masih ingat betul betapa kebingunganku saat itu. Apa maksud ibu dengan kalimat itu? Aku tak bisa memahami sepenuhnya, tetapi saat itu aku hanya mengangguk, mendengar doa dan nasihat ibu.
Kini kusadari ilmu itu ringan untuk dibawa kemana-mana, sementara harta hanya beban jika tanpa makna. 6 Tahun menempuh pendidikan di Pesantren dan 3 tahun pengabdian. Bukanlah waktu yang sebentar, seorang anak laki-laki yang dulu tersendu-sendu menangis dan merengek jajan saat ini sudah besar dan dewasa. Sosok ibu yang selalu menjadi penengah di antara masalah yang kuhadapi.
Hidup sering kali menghadirkan kisah yang tak terduga, tak selalu sesuai dengan rencana yang kita buat. Salah satunya adalah perjalanan panjangku yang dimulai dengan cita-cita besar untuk melanjutkan studi di universitas Timur Tengah. Sejak SMA, aku sudah menaruh harapan tinggi untuk bisa melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Kairo atau Universitas Tripoli Libya yaitu dua universitas yang sudah lama aku idamkan.
Sampai datangnya, waktu ketika ku meminta izin menempuh pendidikan dan bimbingan belajar Timur Tengah di Pesantren Al-Kautsar Cianjur. Salah satu mediator Universitar di Timur Tengah. Demi mewujudkan cita-citaku untuk bisa menempuh di Al-Azhar Kairo atau di Universitas Tripoli Libya yang sudah didamba-dambakan semenjak SMA. 2 dari 3 delegasi Pesantrenku diterima di Al-Azhar dan aku ditakdirkan untuk studi di Indonesia.
Meskipun awalnya kecewa, aku segera menyadari bahwa inilah takdir yang terbaik untukku. Terkadang, takdir tidak sesuai dengan rencana kita, tetapi dalam setiap keputusan yang diberikan-Nya, selalu ada hikmah yang lebih besar.
Kini aku sadar, bukan tentang ke mana aku ingin pergi, tapi ke mana Allah ingin membimbingku. Sebab takdir-Nya selalu lebih baik dari rencanaku. Timur Tengah bukanlah takdirku saat itu, bukan karena aku tak pantas, tetapi karena Allah telah menyiapkan jalan lain yang lebih baik, yang mungkin belum kumengerti saat ini. Sebab setiap langkah yang tertunda bukanlah kegagalan, melainkan cara-Nya mengarahkan hati, mendewasakan jiwa, dan menuntun pada takdir yang lebih indah di waktu yang tepat.
Setiap kali aku bercermin, sering kali aku mendengar orang berkata, “Kamu benar-benar mirip ibumu.” Awalnya, aku mengira itu hanya karena bentuk wajah atau ekspresi yang menyerupainya. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa kesamaan itu bukan hanya soal fisik. Cara berbicara, gestur, bahkan kebiasaan kecil yang kulakukan, ternyata tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan ibu selama ini.
Setiap akhir pekan, ibu selalu mengajakku ke kebun. Bukan hanya untuk menanam atau memanen hasil bumi, tetapi juga untuk mengajarkan banyak hal yang mungkin tidak diajarkan di sekolah. Di kebun itu, aku belajar tentang kerja keras, ketekunan, dan yang paling penting, tentang keikhlasan memberi.
Aku pernah bertanya, “Bu, itu untuk apa? Kok banyak sekali mau dibawa ke mana? Siapa yang makan?”
Ibu hanya tersenyum, lalu menjawab dengan lembut, “Untuk ibu bagikan ke tetangga dan jamaah masjid pas Maghrib.”
Jawaban itu sempat membuatku terdiam. Aku tahu ibu bukan orang kaya, yang bisa membagi-bagikan uang layaknya orang mempunyai banyak uang. Tapi ibu tidak pernah ragu untuk berbagi. Baginya, memberi bukan soal seberapa banyak yang kita punya, melainkan seberapa besar ketulusan yang kita sisihkan untuk orang lain.
Kini, semakin dewasa, aku mulai memahami bahwa warisan terbaik yang ibu tinggalkan bukanlah harta atau benda, tetapi nilai-nilai kehidupan yang tertanam dalam diriku. Seorang yang membawa keteladanan, kasih dan sayang kepadaku yang mungkin belum tentu orang lain mendapatkan hal yang sama.
*_Bersambung_*
Teks masih terus berlanjut, natikan launching bukunya “Ibu”. Sebuah karya antologi santri PP. Darun Nun Malang.